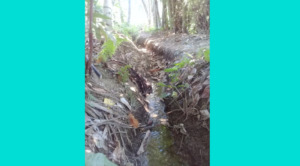Pilkada “Restoratif”: Raih “Emas”, Buang Cemas! (Bagian 2-selesai)
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Senin, 5 Agt 2024
- print Cetak

Oleh: M Ludfan Nasution
Era Otda
Keadaan pada awal Era Otda (Otonomi Daerah) pun nampaknya tak jauh berbeda. Para keturunan raja yang menyebut diri sebagai “anak ni raja, anak ni namora” muncul dan mendapat peran kunci. Klaim wilayah untuk memekarkan kawasan Mandailing, Tanah Ulu (Muarasipongi) dan pesisir Natal pun menuntut pengakuan dan penguatan dari tokoh-tokoh yang kemudian dapat sebutan “pemangku adat”.
Intinya, ini menjdi hal vital dan perlu viral, luas wilayah administratif Kabupaten Mandailing Natal yang dipisahkan dari Kabupaten Induk Tapanuli Selatan tidak lepas dari eksistensi harajaon Mandailing sebelumnya.
Makanya, pemangku kepentingan (formal) saat ini harus tahu diri. Jangan arogan pada saat punya akses langsung pada kekuasaan formal hari ini (eksekutif, legislatif dan yudikatif).
Dalam perjalanan daerah otonom baru (DOB) itu, sejarah juga mencatat, para pemangku adat “rela” hanya mengurusi adat yang makin “usang” tanpa struktur, tanpa anggaran dan tanpa kantor selain serambi Rumah Dinas Bupati waktu itu.
Kausalitas Sejarah
Goresan spekulatif sejarah itu juga membentuk kausalitas yang logis sebagai berikut ini:
Budaya tradisional sudah bertemu dengan modernisme. Efeknya, sangat buruk. Pada fase tertentu, kita dipaksa secara provokatif dan agitatif untuk mengagumi modernitas. Sialnya, kita pun mau dan menanggalkan sebahagian nilai-nilai luhur dan adi luhung budaya kita sendiri.
Dalam pertemuan budaya lokal dan budaya moderen (asing), yang terjadi adalah penggantian, bukan perkawinan atau akulturasi. Kita ganti tata yang lama dengan yang baru, sembari meminggirkan atau menyingkirkan siapa pun yang kita anggap “musuh” (out group).
Akibatnya kemudian, lebih fatal. Bukan saja kita harus mempelajari dan menyerap budaya asing itu hingga menjadi ajaran-ajaran yang mendominasi kepala kita. Faham baru itu juga menjadi poin-poin pertimbangan praktis dalam bidang-bidang baru kehidupan yang seakan terpisah dan berdiri sendiri.
Budaya moderen menjadi pola perilaku parsial yang menguasai bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi. Namun, budaya tradisional yang masih mengakar lekat di dalam diri kita menjadi sejenis tameng sehingga kita tak dapat memahami dan menguasai sepenuhnya varian-varian (anakan) modernisme itu.
Ekonomi liberal dengan postulat “modal minimum untuk meraup untung maksimum” misalnya, hanya membuat kita jadi bak binatang ekonomi yang ujung-ujungnya selalu terengah-engah dalam transaksi demi transaksi, termasuk ketika SDA kita ditukar berdasarkan nilai mata uang Dollar dengan produk teknologi murahan dan mahal (tak sebanding, rugi).
Begitu juga dalam pendidikan. Kearifan yang seharusnya menjadi ruh dan napas program pendidikan perlahan-lahan tercampak. Budaya lokal yang dipaksa stagnan menjadi barang usang dan perangkat pelayanan pariwisata belaka. Sedang pendidikan dipacu bergerak progresif mengejar tawaran kemapanan modern. Keduanya berjalan masing-masing. Jika bukan berbenturan, setidaknya saling meninggalkan.
Kearifan tradisonal dan semua variannya seakan tertinggal jauh di dalam tumpukan sejarah sebagai etalase pariwisata (tontonan). Sebaliknya, pendidikan menjadi jalan pintas untuk mendapatkan kearifan lain yang lebih potensial untuk berkuasa, termasuk dalam “merebut” uang negara dan menjadi kekuatan baru yang bersifat oligarkis.
Demikianlah masyarakat Madina juga seperti terus terbelah. Makin tercerai-berai berebut kuasa politik.
Sebagian menjadi kelompok dalam kuantitas yang kecil mewarisi keluhuran budaya Mandailing dengan hampir tanpa rasa bangga dan tanpa rasa percaya diri (minder).
Sedang yang lain membentuk kelompok atau koalisi berbeda dalam kuantitas sangat besar. Selain meraih gelar-gelar terhormat dan memiliki rasa bangga dan rasa percaya diri yang bahkan over (berlebihan), mereka pun bergandengan tangan dengan para politisi dan tampil sebagai pelaku-pelaku pembangunan dalam struktur trias politik (eksekutif-legiskatif-yudikatif) tingkat kabupaten.
Pun setelah sejumlah cendikiawan dunia Barat diam-diam menyimpan dan mempublikasi kekaguman terhadap nilai-nilai lokal (kearifan tradisional, pengetahuan atau kecerdasan lokal), kita justeru masih terbius dan makin terobsesi dengan “mitos” modernisme.
Tragisnya, ketika sebagian kecil masyarakat tersadar dan ingin kembali ke adat dan budaya lokal Madina, tradisionalitas yang tersisa di sentra-sentra upaya pelestarian adat dan budaya yang marginal (terpinggir) sudah jauh menciut. Banyak yang hilang atau hancur.
Mestinya, seperti Bangsa Jepang yang secara cerdik membuat terobosan budaya (1866), kita segera melakukan restorasi sebelum seluruh bangunan budaya tradisional itu hilang tanpa jejak yang otentik.
Memang, kita masih bisa menemukan realitas organisasi parkahanggian dan metode rapat berupa marpokat atau marsipulut. Masih ada praktek marsali yang tak ada dalam ekonomi kapitalis. Walau nyaris terkikis juga, masih ada praktek marsialap ari dan manyaraya dalam pertanian. Pun kegiatan gotong royong mambasu dahanon dan marsoban di horja siriaon.
Hanya saja, jika restorasi itu jadi pilihan strategi dan pendekatan budaya, kita perlu men-camkan bahwa restorasi itu hanya akan berhasil apabila kita memiliki kesadaran dan keberanian untuk secara perlahan dan pasti berkenan menggeser lambang-lambang kearifan tradisional dari yang sebelumnya marginal (terpinggir) ke posisi yang strategis dan sentral.
Harus kita akui pula, bahwa tokoh-tokoh yang masih merawat kesadaran, kecerdasan dan keberanian untuk melakukan restorasi budaya Mandailing Natal itu sudah tak banyak. Hanya sebahagian kecil dari kalangan pemangku adat (harajaon). Selain itu, ada juga sejumlah pahlawan restorasi yang nantinya datang bergabung secara personal dari luar tradisi dan struktur politik formal. Kedua kategori pegiat restorasi itu belum terorganisir sebagai satu kekuatan.
Mereka juga belum tentu bisa berbuat banyak. Tergantung pada, setidaknya, dua faktor: 1) keteguhan atau kegigihan (tenasitiy) dari tokoh-tokoh pendukung restorasi dan 2) besar-kecilnya pintu yang kita buka untuk restorasi itu.
Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, istilah restorasi itu sudah memasuki fase budaya massifikasi melalui struktur politik dan birokrsi. Istilah itu kita temukan dalam slogan sebuah partai politik dan dalam satu pendekatan penegakan hukum formal bertitel restorative justice.
Kalau kita cermati, kedua model restorasi itu senada atau mirip dengan apa yang kita sebut sebagai gerak budaya akulturasi/kulturasi. Arah kerjanya memang berbeda, tapi muaranya sama: terciptanya kolaborasi dan harmonisasi untuk mengatasi kegagalan sektoral masing-masing.
Ide restorasi nampaknya datang dari struktur modernisme itu sendiri, seperti partai dan birokrasi itu. Sedang akulturasi lebih terkesan sebagai gerakan yang datang dari kalangan pemangku adat atau pewaris tradisi.
Pandangan ini seyogianya menjadi pra-kondisi dan perangkai semangat dan tekad restorasi yang nampaknya sudah berlangsung di momentum Pilkada kelima Madina. Kontestasi yang terjadi bisa bersifat restoratif dengan lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangan budaya lokal (tradisonal).
Buang Arogansi
Kembali ke awal artikel ini, sisa kearifan budaya Mandailing masih cukup untuk menghargai sejarah dan kekinian sebagai batang tubuh yang utuh dari peradaban kontemporer yang ada di Mandailing Natal. Sejumlah budayawan bukan saja merasa bangga dengan tradisi-tradisi luhur yang diwarisinya, melainkan juga cukup sabar untuk terus mempromosikan serta mengajarkan nilai-nilai budaya secara lebih menyeluruh selaras dengan nilai agama yang ada.
Maka, selagi masih ada budayawan yang siap berjuang dalam kerangka restorasi dan akulturasi/kulturasi untuk kejayaan Mandailing Natal, maka kita harus siap untuk:
Membuang sikap arogansi (songong) yang selama ini memarginalkan sejarah budaya dan mengabaikan ajaran agamanya sendiri.
Membuka pemikiran untuk melihat dan menimbang kembali hal lain dari yang sudah kita tahu atau sudut pandang lain, yang belum masuk dalam daftar pengetahuannya (ilmu); dan
Menunggu isyarat dan aba-aba dari para budayawan tangguh Madina, kemana arah dan bagaimana pola restorasinya.
Boleh jadi, para budayawan visioner itu akan menemukan gagasan besar narasi akbar “Patujoloon Mandailing Natal, Standar Baru Kemajuan Daerah”. Mungkin juga akan terjadi diskusi sebelum melebur jadi satu dalam kepemimpinan Ketua Program H. Ivan Iskandar Batubara.
Selanjutnya, para budayawan akan membuat pola untuk melaksanakan restorasi dan akulturasi/kulturasi secara terencana dan berkesinambungan.
Restorasi “Kotak Kosong”
Spirit untuk melakukan restorasi dan akulturasi/kulturasi itu harus pula menemukan momentum pada Pilkada kelima Madina (tahun 2024). Evaluasi total atas capaian empat kali kontestasi Pilkada Madina memberikan satu kearifan tersendiri. Itulah satu paradigma berpikir untuk mewujudkan hasil yang lebih baik, peradaban yang luhur dan unggul.
Dengan orientasi yang baru dan standar nilai yang baru, paradigma itu menciptakan pola-pola kultural dalam menyikapi Pilkada kelima Madina, 2024 ini. Dalam memilih kandidat, kita tidak begitu saja hanya simpati dan mendukung satu paslon. Yang terpenting, kita tidak lagi terjebak dalam babak-babak Pilkada itu.
Sebagai pemilih, kita harus menjadikan Pilkada yang lahir dari rahim modernisme sebagai sarana formal. Sejatinya, ada paradigma dalam menimbang semua tahapan Pilkada dan biografi semua kandidat. Yang harus dimenangkan adalah paslon yang muncul dari dan untuk gerakan restorasi dan akulturasi/kulturasi budaya Mandailing Natal.
Pun jika nantinya muncul hanya satu kandidat dan melawan “kotak kosong” karena KIM (Koalisi Indonesia Maju) dari Jakarta sana membuat plot yang cenderung begitu, kita harus siap. Siap bersinergi dan meloncat lebih tinggi!
Tak perlu lagi kajian dan diskusi yang menghasilkan tuduhan bahwa “kotak kosong” itu anti-demokrasi atau anti-klimaks. Sebaliknya, hasil restorasi itulah emas yang kita cari. Mari kita genggam. Yang lainnya, hanya rasa cemas, maka kita buang sajalah. Kita berdinamika dalam gelombang Pilkada Restoratif. *
Muhammad Ludfan Nasution, jurnalis freelance, alumni IISIP Jakarta dan Anggota DPRD Madina 2014-2019.
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)