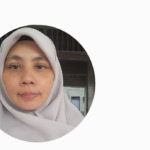Fatwa Pujangga
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Jumat, 5 Okt 2012
- print Cetak
Pengantar
MUARA SIPONGI adalah nama suatu tempat pemukiman penduduk di bagian paling selatan dari banua (wilayah) Mandailing. Letaknya tidak jauh dari suatu tempat pemukiman lain bernama Ranjobatu, yang dikenal sebagai daerah perbatasan antara wilayah Mandailing dan Minangkabau. Keadaan alam di Muara Sipongi didominasi oleh perbukitan dan hutan, yang berhawa sejuk dan udaranya cukup dingin pula. Muara Sipongi ini juga dilewati oleh beberapa anak sungai, yang salah satunya bernama Si Pongi. Kesemua anak sungai itu berinduk pada sungai Batang Gadis yang hulunya berada di kaki Gunung Kulabu, Pakantan. Muara Sipongi berjarak sekitar 65 kilometer ke arah selatan dari Panyabungan, atau jaraknya kurang lebih 25 kilometer dari Pasar Kotanopan.
Perjalanan dari Kotanopan ke Muara Sipongi dapat ditempuh sekitar ¾ jam dengan mengendarai sepeda motor atau mobil angkutan umum. Sepanjang perjalanan banyak dilewati tikungan karena jalan ke sana berkelok-kelok. Jalanan beraspal yang berliku-liku itu terdapat di sisi samping bukit-bukit kecil yang berjejer tiada putus-putusnya, dan di bawahnya terdapat pula sungai Batang Gadis yang airnya mengalir cukup deras, bagaikan sebuah ular besar dan panjang yang sedang melata meliuk-liuk. Mulai dari Kotanopan, dalam perjalanan dapat dirasakan udara yang sejuk, dan terasa semakin sejuk lagi ketika mulai mendekati Muara Sipongi karena Muara Sipongi berada di atas perbukitan, yang letaknya jauh lebih tinggi dari atas permukaan laut ketimbang Kotanopan. Dengan latar pemandangan alam yang indah, sejauh mata memandang, ditambah pula dengan udaranya yang sejuk dan dingin, bisa jadi akan terbersit sebuah kalimat pendek di dalam benak kita: “secangkir kopi panas”. Ya, tepat sekali! Lalu, kenikmatan pun akan dapat direguk sejenak bila di depan mata sudah tersaji secangkir kopi Pakantan, adalah kopi arabika yang terkenal harum dan enak sejak duhulu kala sampai sekarang, hingga ke manca negara.

Negeri-Negeri Kecil di Pedalaman Sumatera
Di kawasan Mandailing Julu, Kotanopan adalah sebuah “negeri kecil” yang dipandang cukup penting bagi orang-orang Mandailing yang bermarga Lubis karena memiliki nilai-nilai historis. Marga Lubis ini memiliki Ompu Parsadaan (satu nenek moyang) bernama Namora Pande Bosi, yang menurut kisahnya adalah cucu dari seorang nakhoda kapal laut bernama Angin Bugis dari Pulau Sulu, Sulawesi. Menurut keyakinan mereka, di sekitar Kotanopan itulah dahulu putra kembar dari Namora Pande Bosi, yaitu Si Langkitang dan Si Baitang untuk pertama kalinya membuka satu tempat pemukiman baru. Keduanya membuka pemukiman di situ sesuai dengan titah sang ayahanda, bahwa apabila dalam pengembaraan ke wilayah Mandailing Julu mereka menemukan suatu tempat di mana terdapat dua buah sungai yang muaranya saling bertentangan, maka di tempat itulah mereka harus membuka perkampungan baru. Tempat ini kemudian dinamakan Muara Patontang, artinya tempat pertemuan muara Aek Singengu dari arah barat dan Aek Singangir dari arah timur. Muara dari kedua anak sungai tersebut saling berhadapan dan sama-sama bermuara ke sungai Batang Gadis. Selanjutnya, tempat pemukiman baru yang bernama Muara Patontang tersebut dinamakan Huta Panopaan, yang lama-kelamaan namanya menjadi Huta Nopan, dan akhirnya disebut sebagai Kotanopan. Dari sinilah Si Langkitang pergi menuju suatu tempat yang kemudian dinamakan Si Ngengu. Selanjutnya dari Si Ngengu inilah keturunannya menyebar dan menjadi raja-raja bermarga Lubis di beberapa tempat-tempat pemukiman baru seperti Simpang Tolang, Sayurmaincat, Tambangan, dan lain-lain. Sementara itu saudara kembarnya Si Baitang melanjutkan pengembaraan yang lebih jauh ke arah selatan. Dikemudian hari keturunannya juga menyebar dan menjadi raja-raja bermarga Lubis di tempat-tempat pemikiman baru seperti Huta Dangka, Tamiang, Huta Pungkut, Manambin, Huta Godang, dan yang lainnya.

Sejak beberapa abad yang lalu, penduduk yang mendiami Muara Sipongi adalah Alak Ulu (orang Ulu) dan Alak Mandailing (orang Mandailing). Orang Ulu secara berkelompok bermukim di beberapa tempat pemukiman seperti Bandar Panjang, Koto Baringin, Tanjung Alai, Ranjo Batu, Sibinail, Simpang Mandepo, Kampung Pinang, dan Silogun. Tempat-tempat pemukiman orang Ulu di Muara Sipongi umumnya terletak di bahagian timur dari banua Mandailing, yaitu di jajaran pegunungan Bukit Barisan. Orang Ulu ini mengaku sebagai penduduk asli di Muara Sipongi karena merekalah yang pertama kali membuka perkampungan di desa-desa yang kini mereka tempati. Sedangkan orang-orang Mandailing adalah warga pendatang dan mereka umumnya menempati tempat-tempat pemukiman di bagian barat (Pakantan), seperti Huta Julu, Huta Gambir, Huta Lancat, Hura Dolok, Huta Lombang, Huta Toras, dan Huta Padang. Orang-orang Mandailing ini berasal dari daerah Kotanopan dan Panyabungan yang bermarga Lubis, Nasution, dan marga-marga lainnya. Di daerah ini, orang-orang Mandailing sebagian besar beragama Islam, dan sebagian kecil beragama Kristen.
Menurut sejarah asal-usulnya, orang Ulu yang bermukim di Muara Sipongi adalah keturunan kelompok pendatang dari Rao pada abad ke-17. Tampaknya, orang-orang Ulu ini memang mempunyai banyak kemiripan dengan orang Rao yang bermukim di Minangkabau, Sumatra Barat. Sementara orang Rao yang bermigrasi ke tanah Semenanjung Malaya (Malaysia) sejak ratusan tahun lalu, dikenal sebagai orang Rawa (http://terombarawa.blogspot.com). Dan perlu dikatahui bahwa di Panyabungan pun ada “suku” lain yang juga dipandang sebagai penduduk asli, yaitu orang Si Ladang. Di sana mereka hidup bersama dan selalu rukun dengan orang-orang Mandailing. Orang-orang Si Ladang ini bermukim dan bercocok tanam (berladang) di daerah perbukitan di bagian timur Panyabungan. Mungkin, karena itulah barangkali sehingga mereka disebut suku Si Ladang oleh orang-orang Mandailing. Sementara orang-orang Mandailing yang bermukim di Panyabungan ini, kemungkinan besar adalah juga orang-orang yang datang belakangan ke Panyabungan, yang terdiri atas berbagai macam suku-bangsa (kelompok etnik). Dengan dasar pemikiran bahwa mulai dari Pidoli (Piu Delhi), Simangambat, hingga ke Padang Bolak terdapat banyak sekali peninggalan zaman peradaban Hindu, baik berupa candi maupun artifak-artifak kuno lainnya. Menurut cerita-cerita lisan yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat, kesemuanya itu adalah pusat-pusat peribadatan agama Hindu, di mana penganutnya adalah Alak Holing (orang Keling-India) yang bermukim di situ pada masa dahulu, dan pusat-pusat peribadatan agama (peradaban) Hindu ini dinamakan Mandala Holing. Orang-orang pendatang belakangan yang terdiri atas berbagai macam suku-bangsa tadi lalu bermukim pula di situ, dan hidup berdampingan dengan orang-orang Keling (India). Kedatangan mereka ke kawasan itu adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik, karena tanah di kawasan tersebut sudah sejak lama mereka dengar mengandung banyak sere (emas). Di kemudian hari, orang-orang yang hidup dan berkembang (beranak-pinak) dalam lingkup pusat-pusat peradaban Hindu (Mandala Holing) di masa lalu itu dikenal sebagai Alak Mandailing (Orang Mandailing). Untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram, dan harmonis, maka diciptakanlah satu sistem sosial atau adat-istiadat yang sesuai dengan eksistensi mereka yang terdiri atas berbagai macam suku-bangsa, yaitu adat Dalian Na Tolu (tumpuan yang tiga) atau adat Markoum-Sisolkot (adat berkaum-kerabat), yang selanjutnya Alak Mandailing secara keseluruan menjadi Bangso Mandailing (Bangsa Mandailing), yang terdiri atas sejumlah huta atau banua (“kerajaan kecil”) bersifat otonom dengan kepemimpinan tradisional bernama Namora Natoras yang dikepalai oleh Raja Panusunan Bulung, namun akhirnya menjadi suku-bangsa (kelompok etnik) Mandailing, sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945.
Seperti halnya di Mandailing Julu, orang-orang Mandailing yang bermarga Nasution memandang Panyabungan sebagai “negeri kecil” yang bersejarah di kawasan Mandailing Godang. Panyabungan berada tepat di tengah-tengah dataran rendah yang luas dan tanahnya sangat subur untuk tanaman padi, sehingga menarik minat penduduk desa-desa lain untuk pindah ke Mandailing Godang untuk mencari penghidupan yang lebih baik sebagai petani atau pedagang, seperti kepindahan orang-orang Mandailing bermarga Lubis yang mendirikan tempat pemukiman baru bernama Huta Lubis, yang jaraknya sekitar setengah kilometer dari Panyabungan. Untuk kawasan Mandailing, Panyabungan ini dikenal sebagai “lumbung padi” karena memiliki peran penting sebagai penghasil makanan pokok yang cukup berlimpah yaitu padi (beras).
Mengapa “negeri kecil” yang berada di kawasan Mandailing Godang itu diberi nama Panyabungan, sesungguhnya tidak diketahui secara pasti. Namun berdasarkan cerita-cerita lisan yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang, “negeri kecil” itu dinamakan Panyabungan karena “daerah” tersebut sering digunakan sebagai tempat utama untuk menyelenggarakan kegiatan “penyabungan ayam”, yang konon katanya merupakan salah satu kebiasaan dan kesukaan orang-orang setempat di masa lalu. Sementara versi cerita lain mengatakan bahwa “negeri kecil” itu dinamakan Panyabungan karena tepi-tepi dari anak sungai Aek Mata dahulu digunakan penduduk setempat sebagai “Panyabunan”, yang artinya suatu tempat untuk mencuci pakaian dan mandi. Kemudian lama-kelamaan, entah bagaimana prosesnya, perkataan “panyabunan” tersebut berubah menjadi Panyabungan yang digunakan sebagai nama dari “negeri kecil” itu. Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa perkataan “Panyabungan” berasal dari kata “Punjab”, adalah nama dari sebuah negeri di India. Tempat itu diberi nama “Punjab” (“Panyabungan”) karena dihuni oleh para pendatang beragama Hindu dari India (orang Keling), yang dalam bahasa Mandailing disebut Alak K(h)oling.
Namun demikian, bila bertolak dari perspektif lain, ada kemungkinan bahwa nama “Panyabungan” untuk “negeri kecil” itu awalnya dapat pula diperkirakan berasal dari perkataan “Paya Bulan”, yang kemudian berubah menjadi “Panyabungan”. Dugaan kuat ini berdasarkan asumsi bahwa Panyabungan adalah suatu daerah penghasil tanaman padi yang berlimpah, dan “Paya Bulan” juga adalah penghasil tanaman padi yang cukup potensial di Maga, yaitu suatu tempat pemukiman dari orang-orang Mandailing yang bermarga Rangkuti dan Parinduri, di mana kawasan Maga sebagai bagian dari wilayah Mandailing Godang ini, sejak dahulu dikenal sebagai daerah perbatasan antara Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Dalam pada itu, perkataan “paya” yang kurang lebih sama maksudnya dengan perkataan “rura”, yang artinya adalah “semak-belukar yang berair”, adalah tempat-tempat yang digarap penduduk setempat untuk menanam padi. Di kawasan Mandailing Godang, “paya” atau “rura” ini sangat banyak sekali ditemukan dan kemudian digarap penduduk setempat, sehingga kawasan ini memiliki areal persawahan yang cukup luas dan berperan sebagai “lumbung padi” di kawasan Mandailing. Oleh karena itulah Mandailing sering disebut sebagai Tano Rura.

Sebaliknya, kawasan Mandailing Julu tidak memiliki “paya” atau “rura” yang banyak, sehingga di kawasan ini tidak ditemukan areal persawahan yang luas. Penduduk Mandailing Julu hanya bertanam padi pada areal yang sempit di pinggir sungai (batang) dan anak sungai (aek), serta di lereng-lereng perbukitan yang memiliki sumber-sumber mata air seperti simulmulan dan aek rura. Karena penghasilan menanam padi umumnya tidak cukup untuk bahan makanan sepanjang tahun, maka penduduk Mandailing Julu membuka ladang (kebun) di dalam hutan. Di situ mereka menanam tanaman keras seperti pohon karet, kayu manis, kopi, dan cengkeh, yang hasilnya dipergunakan untuk membeli beras dan keperluan hidup lainnya. Ketika hasil tanaman keras mereka itu harganya turun di pasaran, atau terjadinya masa paceklik yang disebut aleon, penduduk Mandailing Julu melakukan kegiatan “mendulang emas” (manggore) di Batang Gadis agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, di beberapa tempat tertentu terdapat areal penambangan emas seperti Garabak ni Agom di Huta Godang-Ulu Pungkut, Tombang Ubi di dekat Muara Sipongi, dan sebagainya. Oleh sebab itulah, selain disebut Tano Rura, Mandailing juga dikenal dengan nama: Tano Sere.
Hingga kini, Panyabungan masih terbagi atas tiga bagian penting, yaitu Panyabungan Julu di bagian hulu, Panyabungan Tonga-tonga di bagian tengah, dan Panyabungan Jae di bagian hilir. Pembagian wilayah Panyabungan yang demikian itu sesuai dengan arah mengalirnya sebuah anak sungai bernama Aek Mata di Panyabungan, yang melintang dari arah timur ke barat dan bermuara ke sungai Batang Gadis. Dalam hal ini, suku-bangsa Mandailing memiliki kebiasaan untuk membagi dan menamai bagian-bagian dari tempat pemukiman mereka berdasarkan arah aliran aek (“anak sungai”). Kebiasaan seperti ini juga terdapat di kawasan Mandailing Julu, seperti tempat pemukiman bernama Huta Pungkut yang terletak di pinggir Aek Pungkut, dibagi atas tiga bagian utama yaitu Huta Pungkut Julu, Huta Pungkut Tonga, dan Huta Pungkut Jae. Begitu pula halnya dengan tiga tempat pemukiman utama yang ada di dekat Aek Tambangan, yang juga bermuara ke sungai Batang Gadis, dinamakan Tambangan Julu, Tambangan Tonga, dan Tambangan Jae.
Panyabungan Tonga-tonga adalah suatu tempat pemikiman yang dipandang cukup penting di kawasan Mandailing Godang karena orang-orang Mandailing yang bermarga Nasution mempercayai bahwa Ompu Parsadaan (satu nenek moyang) mereka yang bernama Si Baroar untuk pertama kalinya bermukim di tempat tersebut. Setelah dinobatkan menjadi raja, Si Baroar diberi gelar Sutan Diaru. Hingga kini masih terdapat Bagas Godang (Istana Raja) dan Sopo Godang (Balai Sidang Adat) di Panyabungan Tonga-tonga. Dari sinilah kemudian keturunan Si Baroar (Sutan Diaru) menyebar menjadi raja-raja yang bermarga Nasution di kawasan Mandailing Godang, antara lain seperti Panyabungan Julu, Panyabungan Jae, Pidoli, Maga, dan sebagainya.
Kalau diperhatikan ada persamaan pola hidup antara orang Si Ladang di Panyabungan dan orang Ulu di Muara Sipongi, yaitu sama-sama bermukim dan bercocok-tanam di dataran tinggi (perbukitan) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bahasa Mandailing, daerah perbukitan disebut tor, sedangkan kegiatan berladang diperbukitan ini dinamakan marhauma. Berbeda dengan kebiasaan dari orang Mandailing pada umumnya yang mengolah tanaman padi di “paya” atau “rura” (dataran rendah) dan di pinggir sungai dan anak sungai dengan sistem irigasi persawahan, berkebun di dalam hutan, serta membuat tempat-tempat pemukiman di tepi-tepi anak sungai. Dalam hubungan ini, sama seperti orang Si Ladang, bahwa penamaan Alak Ulu (orang Ulu) terhadap penduduk asli Muara Sipongi yang bermukim dan bercocok-tanam di daerah perbukitan itu, juga diberikan oleh orang-orang Mandailing. Hal ini sejalan dengan kebiasaan mereka untuk menamai tempat-tempat pemukiman mereka, namun berbeda dengan penggunaan istilah “julu” untuk pembagian sebuah huta (kampung) atas tiga bagian utama, yaitu julu, tonga-tonga, dan jae seperti di Panyabungan. Dalam perkataan “ulu” di sini terkandung makna yang maksudnya “bagian kepala” atau “bagian atas”. Seperti misalnya orang-orang Mandailing yang bermukim di bagian hulu dari Aek Pungut disebut Alak Ulu Pungkut. Orang-orang Mandailing yang bermukim di kawasan Ulu Pungkut ini memang terdapat di bagian hulu dari Aek Pungkut, akan tetapi pemukiman mereka itu umumnya berada di dataran tinggi atau daerah perbukitan, seperti Huta Godang yang pada mulanya terletak di daerah perbukitan (disebut Huta Dolok), yang kemudian dipindahkan ke lombang (“dataran yang lebih rendah”) yaitu Huta Lombang di dekat Aek Pungkut. Jadi, “Alak Ulu” artinya orang-orang yang tempat pemukimannya di bagian hulu dari anak sungai yang letaknya di dataran tinggi atau perbukitan.
Terkait dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, boleh dikatakan bahwa dari satu sisi, kesenian orang Ulu merupakan perpaduan antara kesenian Minangkabau dengan Mandailing. Salah satu kesenian orang Ulu yang cukup dikenal bernama Badendak (“berdendang”), adalah suatu jenis tarian berpasang-pasangan yang diiringi dengan dua alat musik utama yaitu biola dan gendang satu sisi, namun adakalnya juga memakai sebuah seruling bambu. Selain itu juga diiringi nyanyian seperti pantun yang dilantunkan berbalas-balasan (“berbalas pantun”), yang tampaknya agak mirip seperti kesenian Ronggeng dalam masyarakat Melayu. Kesenian Badendak ini biasanya diselenggarakan dalam upacara adat perkawinan, pengangkatan dan pengukuhan seorang pimpinan tradisional orang Ulu yang disebut Datuk, dan dalam konteks yang lainnya. Acara seni Badendak ini biasanya diawali dengan tarian pembuka bernama Patam-patam (“pencak silat”), dan kemudian dilanjutkan dengan Tari Saputangen, Hitam Manis, dan yang lainnya.
Sementara kehidupan sosial-budaya orang Ulu bertumpu pada “Tungku Tigo Sojorongen” atau “Tungku Tiga Sejarangan”. Maksud dari ketiga “tungku” itu adalah adat, hukum, dan kitabullah (Al Quran). Dalam hal ini, orang Ulu memiliki falsafah kehidupan seperti yang ada dalam suku-bangsa Minangkabau yaitu “adat bersendi hukum, hukum bersendi Al Quran”. Dengan kata lain, adat didasarkan pada hukum yang bersumber pada Al Quran. Falsafah orang Ulu ini berbeda dengan falsafah hidup (sistem sosial dan kekerabatan) orang Mandailing, yaitu Dalian Na Tolu (“tumpuan yang tiga), yang menumpukan kehidupan sosial-budaya mereka kepada tiga kelompok kekerabatan yaitu mora, kahanggi, dan anakboru, di mana garis keturunan diperoleh dari ayah (patrilineal), sebaliknya orang Ulu menganut paham matrilineal. Selain itu, masing-masing orang Ulu, Si Ladang, dan Mandailing memiliki bahasanya sendiri, yang sama sekali berbeda satu sama lain. Tetapi interkasi sosial yang terjadi di antara mereka dalam kehidupan sehari-hari, termasuk transaksi bisnis (jual-beli) di pasar pada waktu hari-hari pekan seperti di Muara Sipongi, Kotanopan, dan Panyabungan biasanya yang digunakan adalah saro (bahasa) Mandailing).

Kehidupan masyarakat perbatasan di Muara Sipongi tergolong sederhana dengan karakteristik budaya pertanian tradisional. Pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari ini diperoleh dari hasil panen padi dan juga dari hasil penjualan budidaya kebun tanaman keras di lahan-lahan kering daerah perbukitan. Selain itu, wilayah ini juga dikenal sebagai penghasil “gula merah” yang diolah dari pohon enau, dan “minyak nilam” yang diolah dari sejenis tanaman bernama “nilam”. Sementara di bagian barat (wilayah Pakantan) sejak dahulu terkenal sebagai penghasil kopi dengan kualitas terbaik. Pakantan, pernah dijuluki sebagai negeri Gunung Mas. Sebuah kejayaan yang pernah dialami daerah itu antara tahun 1835-1942. Ini terjadi bersamaan dengan penjajahan Belanda atas Mandailing pada waktu itu. Kejayaan Pakantan yang mewakili Mandailing sehingga mendapat julukan sebagai negeri Gunung Mas itu, tak lain karena hasil kopi arabica-nya yang melimpah-ruah. Kebun kopi yang ditanam di dua tempat, yakni di Pakantan Lombang dan Pakantan Dolok, telah memberikan kemakmuran bagi penduduk setempat karena harganya juga sangat tinggi. Tak heran kalau waktu itu sebagian penduduk Pakantan dapat dengan mudah menyekolahkan anaknya hingga ke Pulau Jawa. Karenanya pula banyak orang Pakantan yang telah menunaikan haji ke tanah suci Makkah, dan tidak sedikit yang menjadi saudagar (toke) di Mandailing Julu. Tetapi, julukan Gunung Mas untuk Pakantan kemudian berakhir seiring dengan masuknya penjajah Jepang pada tahun 1942, yang melarang petani menanam kopi dan juga mengekspornya ke Eropa.
Wilayah Mandailing cukup rentan dari fenomena alam yang menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan penduduk, seperti misalnya gempa, yang dalam bahasa Mandailing disebut lalo. Oleh sebab itulah, tiang-tiang utama dari rumah-rumah penduduk di sana dahulu umumnya disangga dengan batu-batu besar pada bagian bawahnya yang berfungsi sebagai pondasi. Sebagaimana diketahui bahwa Muara Sipongi diguncang gempa berkekuatan 5,6 skala richter (SR) sekitar enam tahun lalu. Gempa tersebut mengakibatkan tanah longsor di Koto Rojo sehingga membuat rumah rubuh dan menimpa 4 orang penghuninya hingga tewas (Tempotinteraktif, “Gempa Sebabkan Longsor di Muara Sipongi, 4 Tewas”, 18 Desember 2006). Namun ratusan tahun sebelumnya, sebuah sumber lain mengatakan bahwa gempa yang cukup mengerikan juga pernah terjadi pada tahun 1892. Keterangan mengenai gempa di masa lalu itu dicatat oleh misionaris Nikolai Wiebe. Misi Wiebe kemudian dilanjutkan oleh Johann Thiessen, yang membuat Muara Sipongi sebagai pusat misi utama disamping Pakantan. Untuk periode 1911-1927, Peter Machtigal bekerja di sana, yang kemudian diserahkan kepada misionaris Jerman (http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/M750.html).
Itulah sedikit gambaran mengenai keberadaan “negeri-negeri kecil” dan keanekaragaman penduduknya di pedalaman pesisir pantai barat Pulau Sumatera, sebagai latar belakang dari tulisan ini. Dan mengenai hal-hal apa yang hendakdipaparkan selanjutnya sesuai dengan judul tulisan ini, adalah sosok dan buah karya dari para pujangga yang lahir di “negeri kecil” bernama Muara Sipongi, yaitu Muhammad Kasim Dalimunte (M. Kasim), kakak-beradik Sanusi Pane dan Armijn Pane, serta Z. Pangaduan Lubis.

Dalam kesusastreraan Indonesia, Muhammad Kasim Dalimunte lebih dikenal dengan nama panggilan M. Kasim saja. Ia adalah seorang penulis novel dan cerpen pada zaman Balai Pustaka. Beliau lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara, pada tahun 1886. Dengan pendidikan sekolah guru, ia kemudian menjadi guru sekolah rakyat hingga tahun 1935. Namun sejak tahun 1922, beliau mulai dikenal sebagai penulis melalui novelnya yang pertama terbitan Balai Pustaka, yakni Moeda Teroena. Dua tahun kemudian (1924) ia memenangkan sayembara menulis buku anak-anak, dan meraih “hadiah pertama” dari Balai Pustaka berupa Arloji Emas. Karyanya itu kemudian diterbitkan dengan judul Pemandangan dalam Doenia Kanak-kanak, yang dalam masyarakat luas lebih dikenal dengan judul Si Samin. Karya-karya sastranya yang lain, yang juga cukup fenomenal adalah Bertengkar Berbisik (1929), Buah di Kedai Kopi (1930), dan Teman Doedoek (1936), yang ketiganya diterbitkan oleh Balai Pustaka, Jakarta.
Kumpulan cerpen Teman Doedoek karya M. Kasim dianggap sebagai kumpulan cerita pendek pertama dalam kesusastraan Indonesia modern. Novel maupun cerpennya bercerita tentang penduduk pedesaan di Sumatera dengan gaya bahasa yang sederhana dan penuh humor. Karya terjemahannya ada dua, yaitu Niki Bahtera (dari In Woelige Dagen karya C.J. Kieviet) dan Pangeran Hindi (dari De Vorstvan Indie karya Lew Wallace), yang masing-masing dirilis pada tahun 1920 dan 1931.
M. Kasim yang lahir di Muara Sipongi ini pernah menetap di Kotanopan. Rumahnya terletak di Sindang Laya, tidak jauh dari Pasanggerahan yang terdapat di Pasar Kotanopan. Pasanggerahan ini adalah sebuah bangunan tempat peristirahatan residen pada masa penjajahan kolonial Belanda dahulu. Rumah M. Kasim yang terletak di Sindang Laya tersebut sampai sekarang masih dihuni oleh keturunanya. Rumah tempat kediaman M. Kasim ini sampai sekarang masih tetap kelihatan kokoh dan terpelihara dengan baik, serta tampak asri karena letaknya berada di dataran yang lebih tinggi dan cukup strategis karena tidak jauh dari Pasar Kotanopan.

Sanusi Pane adalah satu diantara beberapa tokoh sastra Indonesia di era Pujangga Baru. Sastrawan yang dikenal sebagai pembaharu kesusastraan di tanah air kita ini, lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara, pada tahun 1905. Beliau adalah sastrawan yang banyak menyumbangkan perhatian dan karyanya untuk kemajuan kesusasteraan Indonesia, terutama pada periode diantara tahun 1919 hingga kisaran 1940an. Bergelut dengan dunia kesusastraan di tanah air yang ketika itu “tertatih-tatih” di era Penjajahan, namun tidaklah membuat Sanusi Pane kehilangan semangat perjuangannya dalam mengembangkan kesusastraan semasa hidupnya.
Sanusi Pane adalah kakak kandung dari sastrawan Armijn Pane. Keduanya anak dari seorang seniman yang juga adalah seorang guru di Mandailing bernama Sutan Pengurabaan Pane. Sanusi Pane bersekolah di HIS dan ELS yang ada di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kemudian pendidikannya berlanjut di MULO, yang dijalaninya di Padang dan Jakarta sampai selesai di tahun 1925. Setelah tamat, Sanusi Pane lebih memilih meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai guru dengan melanjutkan pendidikannya di Kweekschool (Sekolah Guru) di Gunung Sahari (Jakarta) dan tamat pada tahun 1925, kemudian langsung mengajar di almamaternya tersebut, sampai Sanusi Pane dipindahkan ke Lembang, Jawa Barat. Sebelum mengunjungi India, Sanusi Pane juga masih sempat mengenyam pendidikan tinggi (kuliah) dalam mempelajari ontologi di Rechtshogeschool (1929-1930).
Dalam setiap karya kesusastraan Sanusi Pane, tampak dengan gamblang kalau sejarah- sejarah Nusantara di masa lampau terutama di zaman kebudayaan Hindu-Budha, yang menjadi latar belakang dominan dari setiap karya-karyanya, di mana banyak contoh filsafat dan falsafah hidupnya yang lebih memperbandingkan antara kebudayaan Timur dan Barat, memperbandingkan antara hal jasmaniah dengan kerohanian, juga memperbandingkan banyak hal yang satu sama lain merupakan hal yang sangat bertolak belakang. Mungkin inilah merupakan hal-hal mendasar yang banyak ditemukan Sanusi Pane selama kunjungannya ke India. Bentuk inspirasi seorang Sanusi Pane yang tergambar dalam salah satu karyanya yang berjudul Manusia Baru, yang pada tahun 1940 pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka, Jakarta.
Manakala Sanusi Pane kembali dari kunjungannya ke India, sembari tetap bekerja sebagai guru, ia juga menjadi Pemred majalah Timbul, sebuah majalah yang diterbitkan dalam bahasa Belanda. Semasa hidupnya Sanusi Pane menulis berbagai karangan tentang kesusastraan, filsafat dan politik. Pada tahun 1941, Sanusi Pane diangkat menjadi Pemred Balai Pustaka, Jakarta. Beliau meninggal di Jakarta pada tahun 1968 dalam usia yang ke 62 tahun. Karya-karyanya antara lain: Prosa Berirama (1926), Pancaran Cinta (1926), Kumpulan Sajak (1927), Puspa Mega (1927), sedangkan naskah drama yang berbahasa Belanda yaitu Airlangga (1928) dan Eenzame Caroedalueht (1929). Karya lainnya adalah Madah Kelana (1931), Kertajaya (1932), Sandhyakala Ning Majapahit (1933), Manusia Baru (1940), dan Kakawin Arjuna Wiwaha (Mpu Kanwa, terjemahan dari bahasa Jawa Kuno, 1940).

Kalau mahasiswa Fakultas Sastra USU ada keperluan dan ingin bertemu dengan Z. Pangaduan Lubis di kampus, biasanya pertama-tama mereka akan pergi ke tempat parkir kendaraan roda dua untuk memastikan apakah sepeda motor Honda CB tahun 70an berwarna putih ada diparkir di situ atau tidak. Kalau ada berarti beliau sedang di Kampus untuk mengajar hari itu atau sedang ada keperluan lain. Sebagai salah seorang dosen di Fakultas Sastra, tentu saja para mahasiswa selalu berkentingan dengan Z. Pangaduan Lubis, yang setelah bertemu dengan beliau biasanya mereka sapa dengan sebutan “Pak Pangaduan” saja. Kalau tidak sedang memberi kuliah di dalam kelas, Pak Pangaduan cukup sering duduk-duduk santai sembari minum kopi di kantin Fakultas Sastra bersama koleganya sesama dosen dan juga tentu para mahasiswa. Di situ mereka membicarakan banyak hal tentang “dunia kampus” di Fakultas Sastra USU.
Pak Pangaduan memang sosok yang cukup bersahaja, namun beliau sangat kritis dalam disiplin ilmu pengetahuan, terutama untuk bidang studi yang digelutinya yaitu kesusastraan, teater, musik, atau kebudayaan pada umumnya. Dengan berbagai keahlian yang dimilikinya itu, sehingga tak heran kalau Pak Pangaduan adakalanya disebut banyak orang sebagai sastrawan, seniman, atau budayawan di Sumatera Utara. Satu hal yang cukup menarik dari penampilan keseharian Pak Pangaduan ini adalah adanya sebuah gelang akar-bahar yang melingkar di lengan tangan kirinya, dan di jari manis tangan kanannya tersemat pula sebuah cincin (berbatu akik) yang cukup besar. Tak hanya itu, rambutnya pun gondrong, namun selalu tampak rapi karena beliau rajin meminyaki dan menyisir rambutnya.
Selain mengabdi sebagai dosen luar biasa — tanpa menyandang gelar kesarjanaan apapun — di Fakultas Sastra USU, Pak Pangaduan adalah salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Radio Republik Indonesia (RRI) Medan. Barulah pada tahun 1986 beliau memperoleh gelar sarjana antropologi dari Fakultas Sastra USU dengan karya tulis (skripsi) berjudul Namora Natoras: Kepemimpinan Tradisional Mandailing dan memperoleh nilai cum laude. Setelah itu, beliau diangkat menjadi dosen luar biasa di FISIP USU. Selain itu, Pak Pangaduan juga mengajar (sebagai dosen luar biasa) di Program Studi Etnomusikologi Fakultas Sastra USU untuk mata kuliah “Musik Ritual” dan “Studi Tekstual dalam Nyanyian”.
Sebagai seorang seniman, Pak Pangaduan banyak terlibat dengan para pekerja seni di Sumatera Utara, terutama seni teater. Di bidang seni teater ini, Pak Pangaduan memiliki beberapa karya ciptaannya sendiri berupa “naskah drama”, antara lain seperti Si Sarindan, Rimba Cermin-cermin, Paturun Sibaso, dan Kolak Susu. Begitu juga halnya di bidang sinematografi (film), beliau membuat skenario senetron Janji Namboru (1987) dan Si Lemban (1988). Selain itu, Pak Pangaduan juga cukup banyak terlibat dalam pembuatan film-film dokumenter tentang seni-budaya etnis di Sumatera Utara, bekerja sama dengan TVRI dan TV swasta nasional, antara lain seperti Mararirayo di Tano Mandailing dan Horja ni Namora Natoras. Dalam dunia akademis, beliau menulis sejumlah artikel di media massa, dan membuat makalah yang dipresentasikan dalam berbagai seminar nasional. Buku yang pernah beliau karang berjudul Cerita Rakyat dari Sumatera Utara (1996), Kisah Asal-Usul Marga-Marga Di Mandailing (Yapebuna, 1987), dan bersama Zulkifli B. Lubis menulis buku berjudul Sipirok na Soli: Bianglala Kebudayaan Masyarakat Sipirok (1998). Di bidang kesusasteraan pun Pak Pangaduan berkarya seperti cerpen berjudul Pada Cuaca yang dibuatnya tahun 1973, dan karya prosa berjudul Ribeli 1966 adalah kumpulan sajak bersama sahabatnya Aldian Aripin dan Djohan A. Nasution, serta Surat Cinta dan Nyanyian Anak-anak Miskin (1997) bersama teman karibnya Iswadi. Selain itu, sajak-sajaknya juga dimuat di Harian Kami, Sinar Harapan, dan majalah sastra Horizon. Sedangkan di bidang seni musik, Pak Pangaduan menciptakan lagu-lagu pop Mandailing, antara lain berjudul: Mandailing, Willem Iskander, Bulung Gadung, Lubuk Larangan, dan Jambatan Merah.
Satu hal penting yang perlu menjadi cacatan tersendiri tentang sosok seniman, sastrawan, budayawan, dan antropolog yang bernama Z. Pangaduan Lubis (Pak Pangaduan) ini, adalah kegigihannya untuk memperkenalkan eksistensi kelompok etnis atau suku-bangsa Mandailing di tanah air (Indonesia) dan manca negara. Pak Pangaduan bersama-sama dengan tokoh Pemuda Pancasila H.M.Y. Effendi Nasution (alm), dan sejumlah tokoh Mandailing lainnya di kota Medan, membentuk sebuah wadah khusus untuk orang-orang Mandailing, yaitu Himpunan Keluarga Besar Mandailing (HIKMA). Setelah terbentuk pertama kalinya di Medan, dalam perjalanannya kemudian HIKMA dibentuk di berbagai kota di Indonesia seperti di Jakarta, bahkan di tanah leluhur Mandailing dan juga di Malaysia dibawah pimpinan Abdur-Razaq Lubis gelar Namora Sende Lubis.
Tidak hanya itu, Pak Pangaduan bersama-sama dengan H. Amron Daulae, Zulkifli B. Lubis, Muhammad Bahksan Parinduri, Imsar Muda Nasution, Safrida Lubis, dan yang lain-lainnya membentuk sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pengkajian Budaya Mandailing (YAPEBUMA), yang didirikan secara khusus untuk mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat Mandailing, baik yang bersifat tradisional maupun untuk orientasi pengembangan seni dan budaya Mandailing di masa depan, dengan melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian secara akademis. Untuk itu, Pak Pangaduan bersama-sama pengurus YAPEBUMA lainnya cukup sering mengunjungi tanah leluhur Mandailing. Sedangkan untuk menumbuh kembali minat dan kecintaan masyarakat Mandailing terhadap budayanya sendiri, khususnya di bidang kesenian, YAPEBUMA menyelengarakan beberapa kali “Festival Kesenian Mandailing” di tanah leluhur, seperti di Muara Sipongi, Kotanopan, Panyabungan dan Siabu. Festival kesenian ini diberi nama Pargalanggangan ni Uning-uningan Mandailing dengan menggelar berbagai seni tradisional seperti Gordang Sambilan, Sibaso, Tortor, Turi-turian, Moncak, Uyup-uyup, Ende-ende, lagu pop Mandailing, dan sebagainya. Festival kesenian Mandailing ini dapat terselenggara berkat bantuan pihak sponsor (seperti PT. Kalbe Farma, PT. ALS, dan Yayasan Kehati Jakarta), serta sumbangan dana dari orang-orang Mandailing sendiri.
Mengenai sosok Pak Pangaduan ini, banyak di antara sahabat, rekan, kolega sesama dosen, dan “murid-muridnya” yang tidak mengetahui riwayat hidupnya secara detil, termasuk aku (penulis) sendiri. Beliau kukenal pertama kali lewat seorang teman sekampung yang sudah lebih dulu kuliah di Fakultas Sastra USU, yaitu Zulkifli B. Lubis. Karena Pak Pangaduan juga mengajar di jurusan Etnomusikologi, tempatku menimba ilmu, sehingga lama-kelamaan hubungan kami semakin akrab, dan tidak jarang beliau kukunjungi di rumahnya walau hanya sekedar untuk markombur (ngobrol ngolor-ngidul) saja, di malam hari. Sewaktu markombur inilah Pak Pangaduan memperkenalkan kesenian tradisional Mandailing kepadaku. Meskipun aku lahir dan besar di Mandailing, tepatnya di kecamatan Kotanopan, namun pada awalnya, sungguh, di kepalaku tidak pernah terbersit akan hal itu. Studi kujalani di Etnomusikologi pada mulanya adalah pertimbangan ekonomi semata. Kala itu, biaya studi di situ jauh lebih murah dibandingkan kalau kuliah di perguruan tinggi swasta untuk bidang studi yang kuinginkan. Pilihan pertamaku untuk kuliah di USU adalah Fakultas Ekonomi, dan pilihan keduanya FISIP, tapi ternyata aku diterima di jurusan Etnomusikologi sebagai pilihan ketigaku. Dunia etnomusikologi kumasuki hanya bermodalkan kepandaian bermain guitar yang ala kadarnya saja, karena dalam hal bermain guitar di kampung (Kotanopan) hanya kupelajari secara otodidak, tapi rajin melihat dan meniru gaya permainan guitar dari orang-orang sekampung yang lebih tua dariku, seperti angkang (abang) Mulyadi dari Banjar Sawahan, Papa Dede (Satan) dari Si Ngengu, Kasto dan Indrajit (Kapan) dari Banjar Lombang di Pasar Kotanopan.
Ketika ngobrol dengan Pak Pangaduan untuk kesekian kalinya, suatu saat ada satu hal yang membuatku terkejut ketika beliau membicarakan sosok Ketua Jurusan kami di Etnomusikologi, yaitu Rizaldi Siagian. Katanya padaku: “Biar kau tau Edi, ketua jurusan kalian itu, dulu ia pemain drumer sebuah band yang cukup handal di Medan ini. Tapi pernah kubilang padanya, permainan drum kau itu belum ada apa-apanya itu Rizaldi, jika dibandingkan dengan main musik Gordang Sambilan dari Mandailing!” Mulai sejak itu, kami pun sering berdiskusi tentang seni dan budaya Mandailing dalam berbagai kesempatan, dan mengajakku untuk ikut bergabung di YAPEBUMA bersama-sama dengan teman-teman sekampung lainnya. Di antara sesama teman sekampung yang bergabung di YAPEBUMA, kalau sedang membicarakan sesuatu tentang sosok atau buah pikiran Pak Pangaduan, kami sering menyebut “beliau itu” dengan istilah “Raja i” atau “Baleo i”, sebagai ungkapan rasa hormat dan penghargaan kami kepada Pak Pangaduan. Karena tidak bisa dipungkiri kenyataan bahwa kepada beliau lah kami dahulu sering mengadu dan bertanya tentang banyak hal, yang dalam hal ini secara kebetulan tampaknya memang sesuai dengan nama beliau yaitu Pangaduan, yang artinya “tempat mengadu”.
Pada mulanya, Pak Pangaduan hanya kukenal sebagai orang Mandailing yang kampung asalnya dari Huta Pungkut, tepatnya Huta Pungkut Jae. Tetapi sewaktu pergi bareng ke Mandailing untuk pembuatan film Janji Namboru, produksi TVRI Medan dan Fakultas Sastra USU yang disutradarainya, dimana salah satu lokasi shooting-nya di desa Manambin, Pak Pangaduan mengajakku ke Muara Sipongi. Setelah berada di sana seharian, barulah kutahu bahwa Pak Pangaduan sebenarnya lahir dan bernjak besar di Muara Sipongi. Rumah orangtuanya tidak jauh dari Pasar Muara Sipongi. Kalau dari arah Kotanopan, rumah itu berada di sebelah kiri dan letaknya di pinggir jalan raya. Ketika itu, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, dan rumah tersebut dihuni oleh saudara perempuannya. Di sinilah Pak Pangaduan bercerita kepadaku kalau beliau sebenarnya adalah putra kelahiran Muara Sipongi. Di “negeri kecil” ini, ia lahir pada tahun 1937, dan menamatkan sekolah rakyat (SR) di situ. Setelah bersekolah di SMP, entah bagaimana kejadiannya, ia diangkat menjadi anak oleh sebuah keluarga bermarga Lubis dari Huta Pungkut Jae. Setelah tamat SMP, Pak Pangaduan merantau ke Medan, kemudian beliau melanjutkan dan menamatkan sekolah SMA di Tano Doli (Tanah Deli) itu. Semasa bersekolah di SMA (1956) ia sudah aktif menulis dan dimuat di beberapa surat kabar di Medan. Beberapa tahun setelah tamat SMA, Pak Pangaduan memasuki “dunia seni” dan “semakin dalam” setelah banyak bergaul dengan kalangan pekerja seni, dimana ketika itu mereka (para pekerja seni) sering “ngumpul bareng-bareng” dan “kongkow-kongkow” di Taman Budaya, Medan. Mulai dari sinilah Pak Pangaduan dikenal sebagai seorang penyair (sastrawan) dan juga seorang seniman yang cukup aktif di bidang seni teater. Selain itu, Pak Pangaduan juga dikenal sebagai seorang wartawan dari salah satu media massa (koran) yang cukup tenar ketika itu di Sumatera Utara.
Dari tahun ke tahun berikutnya, melalui karya-karya seni dan karya-karya akademisnya, Pak Pangaduan semakin terkenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karya seni teaternya yang cukup fenomenal, yaitu Si Sarindan (istilah bahasa Mandailing yang artinya “Si Benalu”), pernah ditampilkan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta (1978); kumpulan cerita-cerita rakyat dari Sumatera Utara diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta; acap kali beliau menjadi nara sumber dan pemakalah dalam berbagai seminar yang mengusung tema-tema kebudayaan, baik di dalam maupun luar negeri.
Akhirnya, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, Pak Pangaduan pun berhenti berkarya karena Tuhan telah memanggil ke haribaan-Nya pada tahun 2011. Di penghujung usianya yang kurang lebih 75 tahun itu, beliau pernah mengalami sakit (stroke). Meskipun akhirnya beliau terpaksa duduk di atas kursi roda karena sakit yang dideritanya, namun ia tetap melayani para sahabat, teman sejawat, dan kaum-kerabat yang datang menjenguk ke rumahnya di Kompleks Wartawan, Pulo Brayan, Medan. Sebelumnya, dua orang isteri yang sangat dicintainya telah lebih dulu berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan isteri pertamanya mereka memiliki tiga orang anak (dua laki-laki dan satu peremuan), sedangkan dari isteri keduanya mereka memiliki dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang diberinya dengan nama Dali, adalah nama panggilan bagi anak laki-laki yang berarti “tumpuan harapan”, dan itu (Dali) sama maknanya dengan istilah Lian yang juga merupakan nama panggilan untuk anak laki-laki di Mandailing.
Gondang 05 Maret 2012
Ditulis Oleh
Edi Nasution

Note: Tulisan ini dibuat untuk mengenang “kepergian” baleo i, Z. Pangaduan Lubis. Semoga karya-karyanya tetap dikenang sepanjang masa dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, amin.
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)